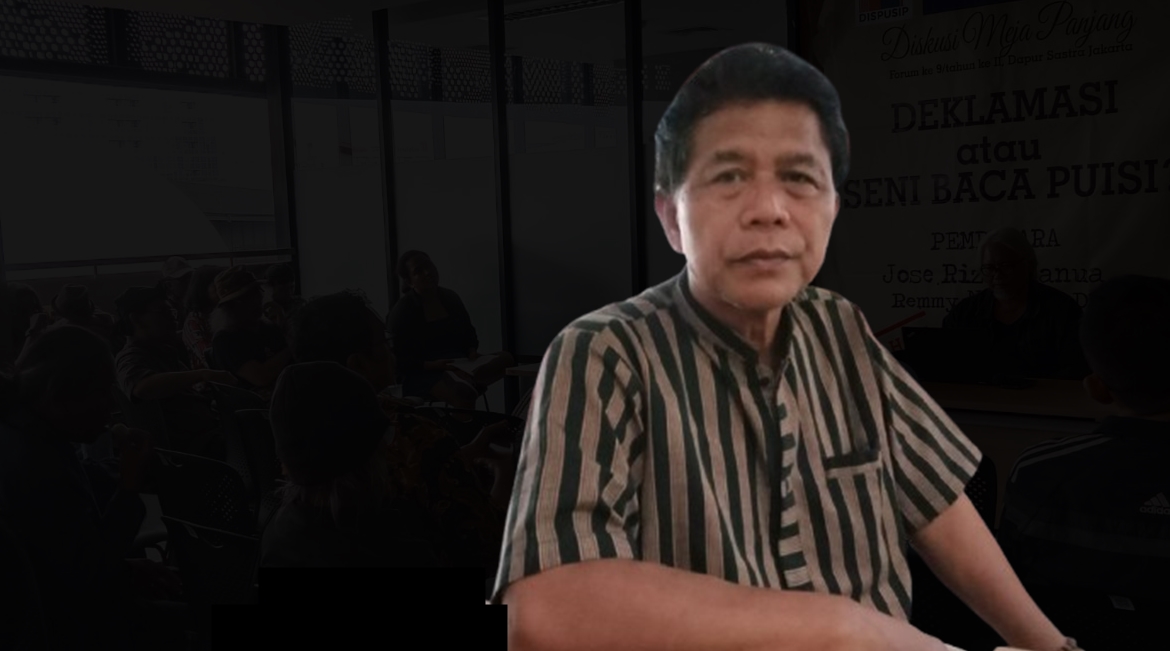PojokTIM – Kesempatan untuk mewawancarai Sunu Wasono akhirnya terlaksana setelah beberapa kali tertunda. Jadwal kegiatan mantan dosen Universitas Indonesia itu memang cukup padat. Selain menjadi pembicara di berbagai forum sastra, Sunu juga dipercaya sebagai juri di sejumlah event yang diselenggarakan Badan Bahasa dan lembaga lain, termasuk juri lomba penulisan cerpen Piala H.B. Jassin 2024.
“Kita ngobrol di kantin saja,” ajak Sunu kepada PojokTIM usai menjadi pembicara dalam peluncuran buku yang digelar Komunitas Literasi Betawi (KLB) di aula PDS HB Jassin, Gedung Ali Sadikin kompleks Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM), Rabu (4/9/2024).
Penulis novel Lenga Tala itu sama sekali tidak terganggu dengan suasana kantin yang ramai. Sapaan para kolega dan sahabatnya dijawab dengan hangat dan ramah tanpa kehilangan fokus pada topik bahasan.
“Kita membutuhkan ruang diskusi yang lebih khusus dengan tema-tema yang dirancang secara serius. Bukan tema-tema yang muncul selintas dari perbincangan. Dengan demikian, tema yang didiskusikan lebih berbobot dan syukur-syukur melahirkan gagasan-gagasan baru yang membawa dampak positif bagi pemajuan kebudayaan, khususnya di bidang sastra,” terang Sunu yang meraih gelar Doktor dari Universitas Indonesia dengan disertasi “Dongeng Lelembut di Rubrik Alaming Lelembut: Ciri, Makna, dan Fungsinya bagi Majalah Panjebar Semangat dan Masyarakat Jawa.”
Berikut rangkuman wawancara PojokTIM dengan Sunu Wasono di pusat kuliner Gedung Trisno Soemardjo.
Seberapa penting riset untuk menulis karya fiksi?
Saya kira sangat penting, terlebih bagi karya fiksi yang menghadirkan sisi lain dari tokoh. Misalnya novel dengan latar Perang Diponegoro 1825-1830. Yang terungkap di permukaan, secara umum, melalui teks sejarah kan seperti itu. Padahal masih banyak hal yang tidak diketahui dari sosok Diponegoro, termasuk intrik-intrik politik yang terjadi di sekitar kerajaan pada waktu itu. Dengan pendekatan sastra hal itu dapat disingkap dan dilukiskan. Untuk mencapai itu, perlu adanya riset, tidak hanya mengandalkan imajinasi atau fantasi. Memang ada yang hanya berdasarkan fantasi seperti (sinetron) yang sering kita tonton di televisi. Namun, jika ingin menulis novel sejarah atau novel budaya yang tujuannya untuk mengungkapkan kepercayaan tertentu, misalnya, perlu riset serius.
Novel-novel top dunia seperti Doctor Zhivago (Boris L. Pasternak), atau karya-karya Ernest Hemingway, dasarnya riset. Laki-laki Tua dan Laut didasarkan pada pengamatan Hemingway terhadap kehidupan nelayan. Meskipun setelah jadi novel isinya berbeda, hal itutidak menjadi masalah karena pengarang novel memiliki cara pandang, ideologi, dan gaya pengungkapan tersendiri. Yang pasti, novelnya didasarkan pada riset, bukan semata angan-angan atau fantasi.
Novel yang tidak didasarkan pada riset, akan terlihat dari deskripsi latarnya, apalagi jika masuk ke latar psikologi dan karakter tokoh-tokohnya. Pembaca yang jeli akan tahu apakah novel itu melalui riset atau hanya fantasi penulisnya. Misalnya, dalam sebuah novel diceritakan awalnya si tokoh suka kelonan, tapi kemudian tidak suka lagi. Perubahan perilaku seperti itu hanya bisa ditangkap oleh penulis fiksi yang memahami budaya. Dengan pengamatan dan riset, ia bisa menangkap perubahan tersebut. Perubahan “kecil” itu menyiratkan adanya dinamika tertentu pada masyarakat yang menjadi objek garapan karya fiksinya. Baca saja karya-karya Umar Kayam, seperti Sri Sumarah, Bawuk, dan Para Priyayi, juga karya Ahmad Tohari, khususnya Ronggeng Dukuh Paruk, akan terlihat betapa penulis tersebut mendasarkan karya mereka pada pengamatan dan penelitian.
Apakah tema-tema tradisi masih diminati penulis fiksi?
Menurut saya, masih cukup diminati. Tiga atau empat tahun lalu saya menjadi juri di Badan Bahasa untuk kategori novel. Saya menemukan banyak novel yang memuat tradisi, muatan lokal, seperti tradisi Batak, Madura, dan Bali. Secara kebetulan, karya dengan latar tradisi ini yang menang karena memang kuat secara tema dan penulisannya. Saya melihat, karya-karya fiksi yang berpegang pada tradisi lebih meyakinkan karena akar dan kekuatan kita memang di situ.
Novel-novel wayang yang Anda tulis didasarkan pada pagelaran wayang Ki Narto Sabdo di YouTube. Sementara lakon pewayangan di Jawa umumnya diambil dari teks klasik Mahabharata dan Ramayana. Bagaimana Anda menggubahnya ke dalam novel, misalnya Lenga Tala, agar berbeda dengan teks asli dan lakon dalam pagelaran?
Pada dasarnya Lenga Tala merupakan alihwahana dari lakon yang dibawakan Ki Narto Sabdo dalam pertunjukan yang kemudian diunggah ke YouTube. Tentu saja dalam alihwahana terjadi perubahan, entah penambahan atau pengurangan. Judulnya tetap Lenga Tala, tapi kisahnya secara keseluruhan mengalami perubahan. Wujud pertunjukan wayang sesungguhnya drama yang di dalamnya terdapat berbagai media. Ada musik, suluk, nyanyian, lampu, dan penonton yang juga memainkan peranan penting dalam sebuah pertunjukan seni. Saat dikemas dalam bentuk video yang di-youtubekan, tentu banyak yang hilang. Suasana pertunjukannya tak ada lagi. Lebih-lebih ketika dialihwahanakan menjadi cerita tertulis. Nah, ketika saya alihwahanakan ke dalam novel, semua unsur yang saya sebut itu hilang, tinggal ceritanya saja. Di situ saya harus kreatif. Ada narasi dalang, suluk, dan dialog yang harus saya narasikan, tapi juga ada narasi yang saya dialogkan. Karena suluk, narasi pada adegan jejer, dan lain-lain yang semuanya menggunakan bahasa Jawa pedalangan tidak bisa dihadirkan sesuai dengan aslinya, maka saya ganti dengan cerita.
Apakah bisa dikatakan Anda menjadi “dalang lain”?
Betul. Boleh disebut demikian. Hanya saja saya dalang yang tidak melantunkan suluk, memberi instruksi niyaga dan pesinden. Mas Yanusa Nugroho bahkan menyebut saya “dalang mbeling” di antara tanda petik. Dalang dalam novel wayang harus bisa menguasai tokohnya, menghidupkan ceritanya, dan seterusnya. Meskipun demikian, saya lebih senang menyebut diri saya sebagai narator atau pendongeng saja.
Apakah Anda juga mengubah tema dalam lakon yang dialihwahanakan?
Tidak. Secara tematik saya setia dengan sumbernya. Jika ingin memasukkan sesuatu, yang keluar dari tema,misalnya membahas masalah-masalah sosial, saya melakukannya melalui tokoh-tokoh punakawan sebagaimana umumnya dalam pertunjukan wayang. Saya juga menghadirkan tokoh lain, misalnya Mukidi, Kintaka, Kang Giman supaya konteksnya nyambung dengan kondisi sekarang. Tokoh itu kemudian saya “wongke”, saya orangkan. Jadi, ceritanya tidak hanya seputar kehidupan istana, tapi juga kehidupan di luar istana. Sekadar contoh, misalnya Bambang Kumbayana dalam Lenga Tala, bergaul dengan petani yang mengalami masalah dengan istrinya, rakyat kecil yang terlibat judi sehingga tidak menghargai istrinya, dan lain-lain.
Apa itu yang membedakan karya Anda dengan karya-karya penulis yang juga mengangkat tema pewayangan seperti Sindunata, Satyagraha Hoerip dan lainnya?
Boleh disebut demikian. Sindunata memiliki gaya sendiri, demikian juga Satyagraha Hoerip. Ah, mereka penulis-penulis hebat. Tak usah dibandingkan. Jomplang soalnya. Saya menikmati novel-novel Sindunata. Kemampuan dia menggambarkan karakter tokoh-tokohnya luar biasa. Tetapi saya tidak boleh menjadi peniru yang bersangkutan. Saya harus punya style sendiri.
Raja Jawa banyak mengadopsi tokoh pewayangan baik dalam tindakan maupun kebijakan. Dalam pandangan Anda, seperti apa sebenarnya konsep raja Jawa?
Raja Jawa diibaratkan sebagai pengejawantahan dewa, tuhan. Memiliki kedudukan yang sangat tinggi, memiliki kekuasaan tak terbatas. Ketinggiannya hampir tidak terjangkau oleh orang biasa. Saking dihormatinya, gelar dan sebutannya banyak. Orang biasa memanggilnya Sinuwun, Gusti, dll. Dalam pewayangan juga seperti itu. Seseorang yang datang ke istana tanpa dipanggil oleh raja, bisa bermasalah, terkecuali jika ada kondisi darurat. Karena itu, prajurit yang datang menghadap raja sebelum melaporkan keadaan yang sebenarnya mengatakan tidak ada gajah terlepas ikatannya, atau singa keluar dari kandangan.
Banyak raja Jawa, meski masih berkuasa, tidak lagi dianggap oleh rakyatnya. Apa yang melatari kondisi demikian?
Hal itu biasanya didasarkan pada perilaku sang raja sendiri yang tidak mencerminkan diri sebagai raja, sehingga rakyat menyebutnya telah kehilangan wahyu. Raja di Jawa bisa duduk di singgasana, bisa berkuasa, karena memiliki wahyu. Ketika seorang raja telah kehilangan wahyu maka dia sudah menjadi orang biasa. Tidak lagi berwibawa, sehingga kehilangan kepercayaan dari rakyatnya.
Dalam sistem kekuasaan sekarang, meski tidak lagi berbentuk kerajaan, analogi semacam itu masih berlaku. Misalnya ketika Pak Harto (Presiden Soeharto, red) jatuh. Banyak yang meyakini karena beliau sudah tidak didampingi Ibu Tien sebagai pemegang wahyu keprabon. Ketika Bu Tien meninggal, wahyu keprabonnya loncat sehingga Pak Harto kehilangan kepercayaan dari rakyat.

Sunu Wasono ketika menjadi pembicara pada salah satu diskusi di PDS HB Jassin. Foto: Ist
Terkait maraknya penerbitan dan peluncuran buku, khususnya di PDS H.B. Jassin, menurut Anda, secara kualitas bagaimana?
Saya kira itu efek dari kebebasan sehingga setiap orang bisa menulis, bisa menyatakan pendapatnya dalam bentuk puisi, dan lain-lain. Dulu ada penjaganya yakni sekelompok orang yang dianggap paling paham tentang karya, termasuk menentukan apakah sebuah karya layak dimuat atau tidak.
Kalau sekarang siapa saja bisa menerbitkan asal punya karya dan uang. Akibatnya, banyak karya yang masih sebatas menambah kuantitas. Tetapi saya menganggap maraknya penerbitan buku sebagai hal yang positif. Dari sekian banyak buku yang terbit, pasti akan muncul karya yang bagus dan berkualitas.
Namun demikian, kehadiran editor tetap perlu. Saya juga sering diminta oleh penerbit Teras Budaya untuk menyeleksi karya yang akan diterbitkan. Ini menggembirakan karena sudah muncul kembali kesadaran akan pentingnya editor. Bukan berarti untuk membatasi penerbitan atau menciptakan rezim editor. Silakan juga yang ingin menerbitkan karya tanpa melalui editor. Dua hal ini saya kira bisa berjalan beriringan.
Bagaimana perkembangan ekosistem kesenian di TIM setelah revitalisasi?
Sebagai orang yang pernah merasakan TIM zaman dulu, saya merasa banyak kehilangan. Suasana seperti dulu tidak saya temukan pada TIM yang sekarang. Misalnya dulu kita bisa diskusi di mana saja. Bisa melihat aktor-aktor teater berlatih, atau melihat Putu Wijaya melatih aktornya, sekarang ruang-ruangnya semakin sempit.
Tetapi bagi generasi sekarang, yang tidak menikmati suasana dulu, barangkali tidak masalah karena mereka tidak memiliki pembanding. Jadi, selalu ada dua sisi dari suatu perubahan.
Bukankah sekarang banyak peluncuran buku yang disertai diskusi, khususnya di PDS HB Jassin?
Peluncuran buku di masa itu memang tidak sesemarak sekarang. Sebab dulu lebih banyak diskusi tanpa melibatkan peluncuran buku. Kalau sekarang diskusi hanya menjadi bagian kecil dari acara peluncuran buku. Lebih dominan acara lainnya semisal pembacaan puisi.
Saya kira itu perkembangan baru. Sah-sah saja. Tetapi hendaknya diskusinya jangan dikesampingkan, jangan hanya dijadikan hiasan. Kalau acaranya diskusi ya perbanyak waktu diskusinya. Jika acaranya pembacaan puisi, maka khususkan hanya untuk baca puisi. Kemarin saya usulkan ke Mas Imam Ma’arif (Ketua Simpul Seni Dewan Kesenian Jakarta, red) agar DKJ membuat festival pembacaan puisi, bukan hanya lomba-lomba. Kalau lomba orientasinya tentu menang-kalah. Kalau dalam festival, pembaca puisi bebas berekspresi.
Apakah karena itu sehingga diskusi-diskusi sekarang tidak melahirkan gagasan atau ide-ide besar seperti dulu?
Mungkin saja begitu. Karena sudah tahu diskusinya hanya sebagai pemanis acara, maka narasumbernya pun tidak terlalu serius dalam menyiapkan materi. Kalau dulu misalnya kita mengundang Wiratmo Soekito untuk diskusi 10 tahun Manifes (Kebudayaan). Orang yang datang memang ingin mengikuti diskusi, bukan melihat pembacaan puisi. Beda ketika kita datang ke acara pembacaan puisi, kita memang ingin melihat orang baca puisi. Misalnya dalam acara pembacaan puisi oleh Ibrahim Sattah. Kita benar-benar disuguhi tontonan pembacaan puisi, tanpa direcoki diskusi, paling-paling pengantar biografinya. Jadi, harus ada batas yang tegas.
Bagaimana dengan tema-tema yang muncul dalam diskusi saat ini?
Sudah bagus. Hanya saja tema-tema yang akan didiskusikan mestinya digodok terlebih dahulu oleh tim kecil sehingga diskusinya terarah. Misalnya untuk diskusi Meja Panjang yang diselenggarakan Dapur Sastra Jakarta (DSJ), harus ada kelompok khusus yang mendiskusikan tema-tema tertentu yang relevan dan aktual untuk diangkat. Dan tidak perlu dikaitkan dengan hari-hari besar tertentu, misalnya sumpah pemuda, hari pahlawan atau hari-hari besar lainnya. Pokoknya sastra pure.
Masih ada yang Anda impikan di tengah perubahan teknologi yang begitu cepat?
Saya masih berharap hadirnya media, seperti majalah, khusus sastra. Saya yakin media cetak masih punya pasar, meski jumlahnya terbatas. Saya tidak anti media online. Keduanya bisa saling melengkapi. Sebab minat orang untuk menerbitkan karyanya di media cetak masih tinggi. Hal itu juga tercermin dari maraknya penulis yang membukukan karyanya secara mandiri.
Tahun ini saya menjadi juri untuk menilai puisi para calon penerima dana apresiaisi dari pemerintah melalui Badan Bahasa. Saya menilai puisi dari buku, bukan dari online. Jumlahnya ratusan. Bukan hanya dari generasi baby boomer (1946-1964) seperti saya, namun juga dari generasi milenial yang lahir di era digital. Ini membuktikan gairah untuk menerbitkan buku masih tinggi. Apa pun wujudnya, berapa pun (jumlah) eksemplarnya.
Saya punya keyakinan, penerbitan buku, majalah, tetap diminati. Konon di Jepang, yang teknologinya sudah sedemikian maju, tradisi membaca buku tidak sertamerta hilang. Jadi, saya masih memimpikan hadirnya majalah cetak khusus sastra seperti yang sempat diterbitkan oleh DSJ.