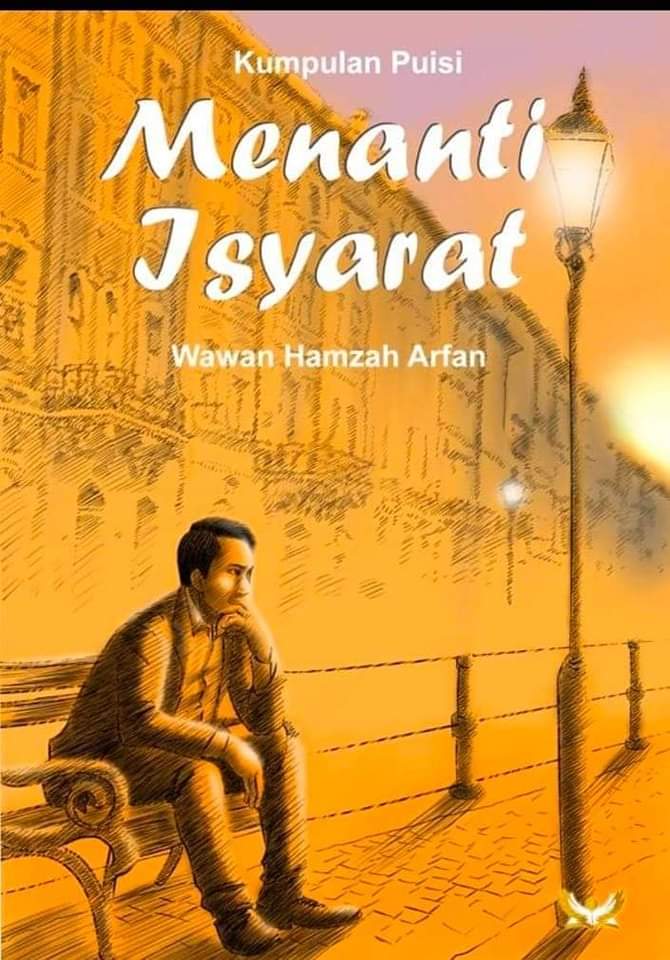PojokTIM – ketika kukembalikan kesunyian/pada batas waktu/terasa ada yang hilang/angan ku melayang/keheningan/tak lagi menyejukkan rasa/kehampaan/menebarkan penat/menyengat hasratku/keterasingan/memburu rinduku/terkapar dalam semak belukar/dan aku hanya bisa bersandar/pada akar yang menjalar/di luar nalar//
langkahku beku/jejakku membatu/gairahku malu-malu/pada hasrat yang merayap dalam penat/menanti isyarat//
dan aku hanya bisa berbagi lewat puisi/menjajakan aroma kerinduan/mengembara/dalam senyummu/sebagai puisi terindah/yang pernah kubaca/dan kurasa
Cirebon, 2021, hal. 54
Dalam keseharian, isyarat bisa diterjemahkan ketika kita menggerakkan tangan, menganggukkan kepala, mengerdipkan mata, atau pun menggoyang-goyangkan kaki. Penerimaan gerakan isyarat itu tergantung dari nalar orang yang membaca gerak tubuh orang lain (bukan dirinya). Yang jadi pertanyaan, apakah isyarat harus dinanti? Sebuah puisi yang bicara tentang sunyi, bunyi dan isyarat tertentu bisa jadi oleh pembaca dan penikmat puisi dapat dinarasikan dengan sudut pandang yang berbeda. Dalam kesunyian tak menutup kemungkinan angan melambung dan melayang jauh. Keterasingan (di tengah keriuhan) memungkinkan seseorang dihadapkan pada kejenuhan dan kepenatan. Bagi seorang penyair, untuk bisa keluar dari kebosanan maupun kejenuhan — mengeksploitasi curahan hati bisa ditempuh melalui puisi. Dan, melalui puisi pula memungkinkan seorang penyair berimajinasi. Atau memanfaatkan gestur tubuh: gerak tangan, kaki, kepala dan badan untuk sekadar lari dari kenyataan — layaknya sedang bermonolog.
Sebanyak 63 judul terhimpun di antologi puisi tunggal, “Menanti Isyarat”. Bagian I diberi judul “Di Antara Puing-Puing Harapan”, menghimpun 17 puisi. Beberapa puisi di bagian I ditulis tahun 1980-an. Seperti puisi ini: “mimpi siang hari bukan tak berarti/ seperti hari-hari memburu waktu/ ganas/ tegas/ tanpa banyak bicara// dunia terpelanting dalam diam/ dengan tubuh telanjang/ suaranya hilang dimakam zaman/ serak-serak kering// hidup/ bagaikan puntung rokok berasap/ dalam asbak” (“Episode Hidup”, Cirebon 1988, hal. 5).
Dan, di bagian II diberi judul “Menanti Isyarat”, menghimpun 46 puisi. Selain puisi berjudul “Menanti Isyarat”, mayoritas di bagian ini puisi ditulis tahun 2000-an. “hampir saja aku tak menyapamu/ ketika situasi dipertemukan suasana/ hanya saling lempar pandang/ berbagi aroma rasa/ mimpikan aku/ atau hanya sedikit sensasi hati/ bagi rindu yang selalu menunggu/ di haltemu yang tak lagi beratap” (“Aku Masih Menunggu di Haltemu”, Cirebon 2013, hal. 32).
Nama Wawan Hamzah Arfan (kelahiran Cirebon, 8 Juni 1963), sesungguhnya bukan nama yang asing. Ia menulis puisi, cerita pendek, juga esai sastra sejak tahun 1980-an di beberapa media cetak nasional. Sejak dulu kami berteman, berkomunikasi melalui surat dan tergabung di HP3N. Dan, kami kembali dipertemukan melalui face book sekitar tahun 2019. Pada bulan Oktober 2021 kami dan beberapa Sastrawan lain bareng di atas panggung GOR, Pekalongan untuk menerima Penghargaan Kesetiaan Bersastra dari Lumbung Puisi Sastrawan Indonesia, yang digagas RgBagus Warsono. Buku antologi puisi tunggal Wawan, “Menanti Isyarat” ini terbit setelah antologi puisi tunggalnya terdahulu, “Perjalanan Berkarat” (2021) — di samping karya tesisnya yang kemudian dibukukan, berjudul “Nilai Religi dalam Puisi Sutardji Calzoum Bachri Pasca-O, Amuk, Kapak” (Penerbit Hyang Pustaka, April 2022).
DATA BUKU
Judul : Menanti Isyarat
Penulis : Wawan Hamzah Arfan
Penerbit : Hyang Pustaka, Cirebon
Tahun Terbit : Maret 2022
Ukuran : 14 x 20 Cm
ISBN : 978-623-99519-8-6
Tebal : iv + 63 halaman