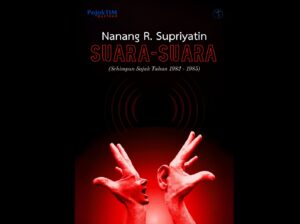Oleh Nia Samsihono
Indonesia sudah 80 tahun merdeka, namun sastra kita sering tampak belum bebas: masih terbelenggu oleh caci maki dan saling menjatuhkan di antara para penulisnya. Padahal, kemerdekaan seharusnya membuat sastra tumbuh subur, bukan mencederai makna merdeka itu sendiri. Sastra seharusnya menjadi ruang kebebasan, tempat gagasan tumbuh dan perbedaan dirayakan. Namun ironisnya, justru di dalam ruang yang mulia ini kerap terjadi praktik yang membelenggu: perundungan antar-sastrawan. Banyak yang mengaku penjaga martabat sastra, tetapi perilakunya justru merendahkan penulis lain, mencibir karya, bahkan mematikan semangat sesama. Fenomena ini menciptakan paradoks. Apa artinya menyebut diri sastrawan bila hanya sibuk menjatuhkan? Apa gunanya nama besar bila hidupnya dipenuhi dengan caci maki terhadap karya orang lain? Menjadi sastrawan bukanlah lomba ego, melainkan ikhtiar memperluas cakrawala kemanusiaan.
Mengapa ada orang yang mengaku sastrawan, namun lebih sibuk merundung ketimbang menulis karya? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, mereka haus pengakuan instan. Menyerang orang lain dianggap cara cepat untuk menjadi sorotan, dibanding membangun reputasi lewat karya yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Kedua, mereka terjebak dalam rivalitas pribadi yang dibungkus seolah-olah sebagai “perdebatan intelektual”, padahal hanyalah pelampiasan dendam. Ketiga, ada yang mulai kehilangan produktivitas menulis, sehingga panggung yang tersisa hanyalah perdebatan dan serangan personal. Sastrawan sejati memahami bahwa kata-kata adalah mata air, bukan racun. Ia memilih bahasa yang menghidupkan, bukan yang mengikis kepercayaan diri orang lain. Pena yang digunakan untuk merundung hanya akan menorehkan luka, baik pada yang diserang maupun pada penulisnya sendiri. Sebab kata yang lahir dari kebencian tidak akan pernah berumur panjang; ia akan layu sebelum sempat dikenang.
Perundungan dalam dunia sastra sejatinya adalah bentuk kemiskinan intelektual. Mereka yang merasa lebih hebat lalu menghina sesama sesungguhnya sedang mempertontonkan ketakutannya sendiri: takut tersaingi, takut kehilangan panggung, takut karyanya tak lagi dianggap relevan. Maka cemooh dijadikan senjata, bukan argumen. Padahal, kritik sejati lahir dari analisis dan niat membangun, bukan dari hinaan kosong. Perundungan dalam sastra bukanlah sekadar sindiran atau kritik tajam. Ia lahir dari niat menjatuhkan martabat seseorang, mempermalukan, atau mengucilkannya. Kritik sejati tumbuh dari cinta pada kebenaran dan hasrat untuk memperbaiki. Perundungan tumbuh dari amarah, iri, atau keinginan berkuasa. Membedakan keduanya bukan perkara sulit—kita dapat merasakannya dari nada dan arah sebuah tulisan.
Sastra tidak pernah tumbuh dari kebencian, melainkan dari keberanian untuk menuturkan kebenaran. Setiap upaya mendiskreditkan penulis lain adalah pengkhianatan terhadap martabat sastra itu sendiri. Penulis yang sejati tahu betapa panjang jalan menuju satu karya; ia tidak akan merundung, melainkan merawat iklim kreatif agar terus hidup. Sastra lahir dari pergulatan batin manusia. Ia merangkai pengalaman, luka, dan harapan menjadi jalinan kata yang mampu menyentuh nurani. Sejak awal, sastra hadir untuk menyatukan manusia dalam pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan orang lain. Namun, di ruang yang seharusnya penuh cahaya ini, kadang kita melihat bayang-bayang: karya sastra yang dijadikan alat untuk merundung.
Kini, ketika ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80, kita ditantang untuk jujur pada diri sendiri: sudahkah sastra Indonesia benar-benar merdeka? Bangsa ini telah delapan dekade lepas dari penjajah, tetapi dunia sastra masih sering terjajah oleh ego, iri hati, dan kesombongan. Perundungan antar-sastrawan adalah perbudakan baru—dan itu jelas mencederai makna kemerdekaan. marilah kita melihat sastra sebagai ruang merdeka bagi semua suara. Ruang yang memberi tempat pada perbedaan, bukan menindasnya. Ruang yang memuliakan keragaman gagasan, bukan memaksakan satu suara.
Menulis karya sastra adalah membangun taman bagi pembaca, di mana ide-ide dapat mekar dan berdialog. Taman itu tidak akan indah jika dipenuhi duri perundungan. Mari kita jaga agar pena kita tidak berubah menjadi pisau. Sebab kemuliaan sastrawan tidak diukur dari siapa yang ia jatuhkan, melainkan dari siapa yang ia bangkitkan. Sastrawan tidak mengikat sesamanya dengan rundungan, sebab musuh terbesar sastra bukan kebodohan rakyat, melainkan kesombongan penulisnya sendiri. Kemerdekaan sastra hanya mungkin lahir bila sastrawan berhenti menjadi penjajah bagi sesamanya. Pada usia 80 tahun kemerdekaan ini, saatnya sastrawan memilih: menjadi cahaya bagi bangsa atau tetap menjadi musuh bagi sastra.
Jakarta, 16 Agustus 2025